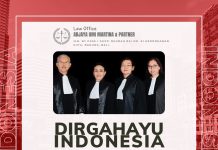Opini, Porosinformatif| Dalam perjalanan panjang sejarah Nusantara, Majapahit sering dijadikan simbol kejayaan politik, ekonomi, dan kebudayaan yang pernah dicapai bangsa ini. Kerajaan yang berdiri pada abad ke-13 hingga ke-15 Masehi tersebut bukan hanya dikenal karena wilayah kekuasaannya yang luas, tetapi juga karena kemampuannya mempersatukan pulau-pulau di Nusantara di bawah satu visi politik yang besar. Melalui kepemimpinan Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaan sebagai kekuatan maritim dan diplomatik yang disegani di Asia Tenggara.
Namun, ketika bangsa Indonesia modern lahir pada tahun 1945, semangat kebangsaan yang diusung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sejatinya merupakan kelanjutan ideologis dari cita-cita Majapahit — Bhinneka Tunggal Ika, persatuan dalam keberagaman. Pertanyaannya kemudian, apakah Indonesia kini telah menjelma menjadi Majapahit modern, atau justru masih tertinggal jauh dari bayangan ideal itu? Esai ini berupaya merefleksikan sejauh mana Indonesia mampu mewujudkan potensi kejayaan Majapahit dalam konteks modernitas, serta mengapa cita-cita tersebut masih terasa jauh dari realitas sosial, politik, dan ekonomi saat ini.
Majapahit: Model Awal Negara Maritim Nusantara
Majapahit merupakan bentuk paling maju dari konsep negara kepulauan (archipelagic state) sebelum lahirnya Indonesia modern. Dalam karya Negarakertagama (1365), Mpu Prapanca menggambarkan struktur pemerintahan Majapahit yang tersusun secara hierarkis namun harmonis, dengan pusat kekuasaan di Trowulan dan daerah-daerah taklukan yang terikat dalam sistem mandala. Wilayah kekuasaannya mencakup sebagian besar Nusantara, dari Sumatra hingga Papua, bahkan hingga semenanjung Malaya dan kepulauan Filipina bagian selatan.
Keunggulan utama Majapahit terletak pada kemampuannya mengelola jalur perdagangan maritim dan menjalin diplomasi antar pulau serta antar bangsa. Nilai-nilai persatuan, toleransi, dan hukum adat menjadi perekat sosial-politik yang efektif. Dengan demikian, Majapahit bukan sekadar kerajaan besar, tetapi juga cikal bakal konsep geopolitik maritim yang kini menjadi dasar eksistensi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
Indonesia: Warisan yang Belum Disempurnakan
Ketika Republik Indonesia berdiri, para pendiri bangsa seperti Soekarno dan Hatta memahami bahwa semangat Majapahit tidak boleh berhenti sebagai kebanggaan masa lalu. Melalui semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, negara baru ini berupaya menghidupkan kembali filosofi kesatuan yang pernah dihidupi oleh Majapahit. Akan tetapi, setelah delapan dekade kemerdekaan, perjalanan Indonesia masih jauh dari bentuk “Majapahit modern”.
Beberapa faktor menjadi penyebab utama keterlambatan transformasi ini. Pertama, Indonesia belum memiliki arah pembangunan jangka panjang yang konsisten lintas generasi. Setiap pemerintahan cenderung menetapkan prioritas baru tanpa kesinambungan strategis. Kedua, orientasi pembangunan masih land-based, padahal kekuatan utama Indonesia seharusnya berada di laut — warisan langsung dari peradaban Majapahit dan Sriwijaya. Ketiga, ketimpangan ekonomi antara pusat dan daerah masih tajam, mengulangi kesalahan klasik pasca-Majapahit ketika daerah merasa terpinggirkan oleh pusat kekuasaan.
Selain itu, budaya politik yang sering diwarnai korupsi dan fragmentasi kepentingan telah menggerus semangat Palapa yang dahulu menjiwai elite Majapahit. Bila Gajah Mada bersumpah untuk mempersatukan Nusantara dengan pengabdian total, maka elite masa kini seringkali terjebak dalam rivalitas kekuasaan jangka pendek. Perbedaan ideologi dan kepentingan sering lebih kuat daripada cita-cita persatuan bangsa.
Dimensi Kultural dan Spiritual: Potensi yang Terlupakan
Majapahit tidak hanya besar karena kekuatan militernya, melainkan juga karena kedalaman nilai-nilai spiritual dan kultural yang menopang sistem sosialnya. Prinsip keseimbangan antara tatwa, susila, dan upacara menjadi landasan moral yang membentuk harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Dalam konteks modern, nilai-nilai ini sejatinya masih relevan untuk membangun etika pembangunan berkelanjutan.
Sayangnya, dalam era globalisasi dan kompetisi ekonomi, dimensi spiritual dan budaya sering terpinggirkan. Indonesia sebagai pewaris peradaban besar Nusantara seharusnya mampu mengintegrasikan kearifan lokal — gotong royong, harmoni sosial, dan penghormatan terhadap alam — ke dalam sistem pembangunan modern. Dengan cara itu, Indonesia tidak sekadar menjadi negara industri, tetapi juga peradaban yang berkarakter dan beretika.
Refleksi: Antara Potensi dan Realitas
Jika dibandingkan dengan cita-cita “Majapahit modern”, kondisi Indonesia kini menunjukkan kontras yang tajam. Kita memiliki sumber daya alam melimpah, posisi geopolitik strategis, serta populasi besar yang produktif, tetapi masih tertinggal dalam hal teknologi, pendidikan, dan efisiensi pemerintahan. Dalam istilah simbolik, Indonesia seperti “Majapahit yang kehilangan kompasnya”: kaya akan warisan, tetapi miskin dalam arah dan disiplin.
Namun demikian, tidak semua gambaran itu pesimistis. Di tengah tantangan, Indonesia menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Munculnya kesadaran maritim, pengembangan teknologi hijau, dan kebangkitan budaya lokal merupakan langkah awal menuju kebangkitan baru Nusantara. Bila diarahkan dengan visi jangka panjang dan tata kelola yang bersih, Indonesia masih dapat menapaki jalur kejayaan yang dahulu dirintis oleh Majapahit.
Majapahit adalah simbol sejarah yang tidak hanya patut dibanggakan, tetapi juga dijadikan cermin bagi masa depan. Indonesia hari ini mungkin belum menjadi “Majapahit modern”, tetapi benihnya masih hidup dalam semangat persatuan, keberagaman, dan kemandirian. Tantangan terbesar bangsa ini bukan terletak pada kekurangan sumber daya, melainkan pada kegagalan menghidupkan kembali semangat kebangsaan yang rasional, etis, dan berorientasi jauh ke depan.
Jika bangsa ini mampu menumbuhkan kembali etos kerja, disiplin moral, dan kepemimpinan yang berjiwa Palapa, maka cita-cita “Majapahit modern” bukan lagi sekadar romantisme sejarah, melainkan arah nyata menuju peradaban Nusantara yang berdaulat, berkeadilan, dan berkarakter global.***